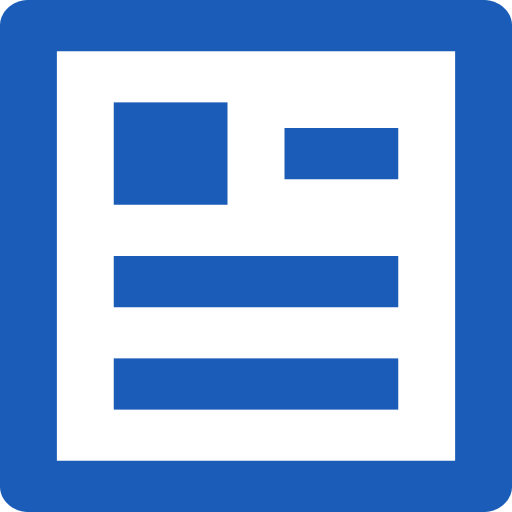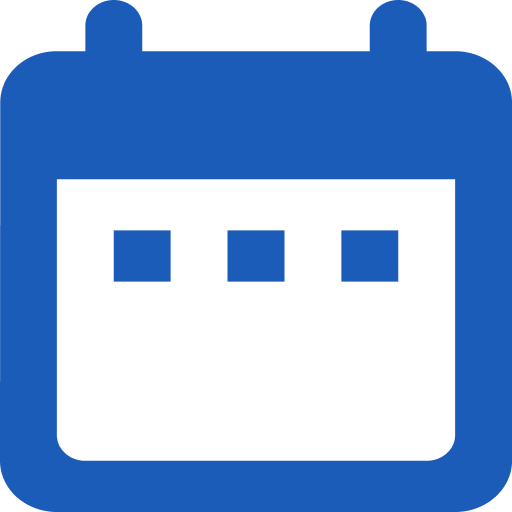Di Antara Label Tradisional dan Internasional, Kita Berutang Kematian
Desa kecil di tengah hutan, ada satu keluarga kecil di dalamnya, seorang anak kecil dan ibunya. Mereka bahagia karena hutan bisa memberi mereka kecukupan hidup. Jika mereka menanam ubi, dengan ajaib ubi itu tumbuh. Bahkan, hutan ini bersedia memberikan mereka buah dan sayur.
Hutan ini seperti mengajari mereka cara menangkap hewan buruan: rusa, babi, burung, atau apa pun itu. Yang terpenting, hewan buruan itu tidak lebih ganas dibanding rasa lapar mereka. Begitulah kira-kira hutan menyuguhkan kenikmatan kecil agar keluarga ini hidup dengan nyaman.
Selain mengajari keluarga kecil ini jauh dari rasa lapar dan haus, hutan ini juga mengajari mereka untuk bertahan hidup. Ketika hujan datang dan sering membuat mereka basah kuyup, mereka berteduh di bawah pohon rindang. Sampai akhirnya mereka menyusun beberapa batang kayu yang di atasnya ditutupi daun. Mereka menyebutnya rumah. Tempat bermukim yang aman bagi mereka.
Di tempat ini, mereka mulai mengenal banyak hal, dari menggesek-gesek kedua batu sampai keluar api sampai bagaimana melenyapkan api itu dengan air. Mereka mengerti dengan memegang api bahwa ada rasa panas yang hadir. Saat mereka menyentuh air, rasa dingin datang. Dari peristiwa sederhana ini mereka mulai memahami sesuatu.
Suatu hari, hutan memberi cobaan bagi keluarga ini. Badan sang ibu tiba-tiba panas sehingga tidak bisa bangun dalam beberapa hari. Si anak panik, lalu berharap pada keajaiban air agar demam ibunya hilang. Mulai dari diguyur, hingga tubuh si ibu direndam di dalam air. Hasilnya nihil, demam itu tidak lenyap. Akhirnya, si ibu harus pergi akibat demam. Duka cita pun datang.
Cerita di atas bukan dongeng, melainkan warisan kemalangan masyarakat pedalaman kita. Mereka dibiarkan hidup dengan diksi "tradisional". Dari mereka, kita banyak berutang. Kita berutang tragedi, kisah, dan nikmat hidup. Tidak hanya itu, kita juga berutang kesehatan kepada mereka.
Utang itu bisa kita lihat dari usaha seorang Edwin Chadwich, manusia yang menjadi pelopor kesehatan masyarakat. Ia tidak lupa mencatat ketertarikannya pada kematian yang terjadi di kota-kota besar di Inggris pada abad ke-19.
Sebelumnya, ada William Farr yang mewariskam kegiatan mencatat angka kematian. Warisan itu tidak lain muncul karena adanya utang kematian dalam sebuah tragedi wabah. Tragedi itu disebut black death (pneumonia karena pes) di Eropa pada tahun 1348, yang menjadi awal mula kegiatan mencatat angka kematian.
Akhirnya, pada tahun 1920 Winslow, guru besar Universitas Yale di bidang kesehatan masyarakat, menyatakan masyarakat harus berusaha menanggulangi masalah kesehatannya sendiri. Dari sini, kesadaran mencegah penyakit kemudian menyeruak.
Di Indonesia, tanggung jawab itu dipegang oleh pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).
Tidak banyak yang menyoroti bagaimana puskesmas hari ini. Di layar kaca, yang cuma berukuran sekian inci, hanya kinerja pelayanan kesehatan di tingkatan rumah sakit yang disorot. Kita hanya punya bekal film dokumenter, semisal Suster Apung (2006) dan Tiga Mama Tiga Cinta (2015), yang dari mereka, terdengar denyut puskesmas kita.
Seperti itulah potret puskesmas kita hari ini: bekal seadanya dengan tanggung jawab segudang. Beradu dengan laju perkembangan teknologi medis. Belum lagi, semakin membanjirinya rumah sakit dengan label internasional.
Jika benar yang dikatakan Pramoedya Ananta Toer dalam romannya, Bukan Pasar Malam, bahwa kalau mengaku tidak punya uang, engkau akan lumpuh dan hanya boleh menonton sesuatu yang engkau inginkan.
Kita cuma punya satu harapan, kehadiran negara harus ada untuk menyudahi kepopuleran diksi "internasional".
Log in untuk komentar