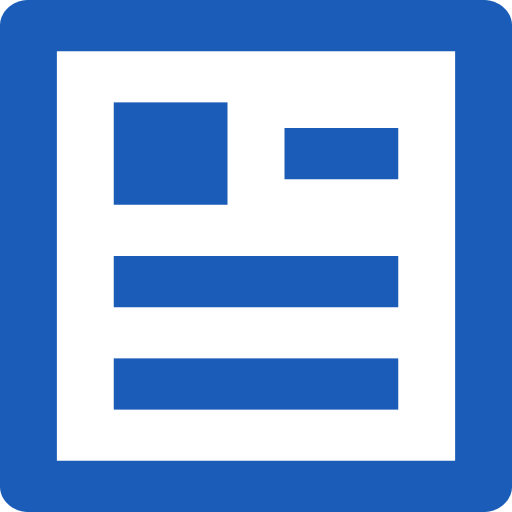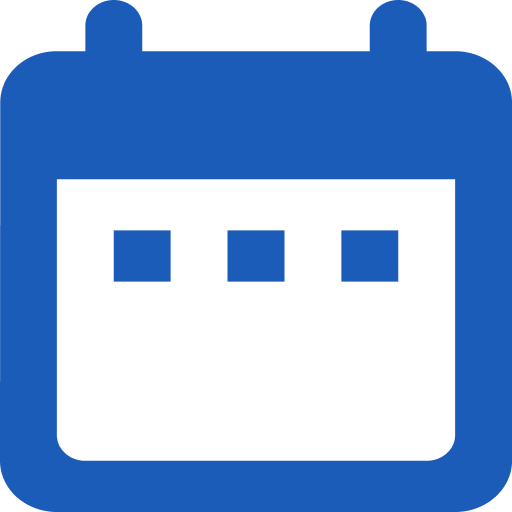Seberapa Penting Peran Advokasi Isu Sosial oleh Dokter di Era Modern?
10-15 tahun terakhir ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat atas isu-isu sosial. Mulai dari ketimpangan gender, akses pendidikan belum merata, disparitas keuangan, perbedaan kualias fasilitas kesehatan dan lain-lain. Arus informasi yang masif, membuat kita bisa mengomentari dan beropini terkait sebuah isu. Hasilnya, advokasi pun tumbuh subur.
Kata "masyarakat" ini menyangkut semua lapisan usia dan profesi, termasuk di dalamnya para tenaga medis dan kedokteran. Kesadaran kolektif atas isu-isu masyarakat terkini membuat mereka kerap menyuarakan pendapat dan kritik dalam status atau cuitan pendek. Ini adalah bibit-bibit aktivisme, bahkan meski hanya berada dalam ranah media sosial.
Hal tersebut juga terjadi di Indonesia dalam banyak kesempatan. Salah satu yang masih diingat oleh publik saat dokter Berlian Idris mempertanyakan inkonsistensi kebijakan pemerintah terkait vaksin COVID-19 pada Juli 2021. Saat itu, perusahaan farmasi milik BUMN mengumumkan wacana penjualan vaksin untuk individu, ketika angka kematian sedang tinggi dan akses vaksin belum merata.
Melalui cuitannya, dokter Berlian menganggapnya berlawanan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada Desember 2020 yang menegaskan bahwa vaksin gratis untuk masyarakat. Cuitan tersebut mendapat lebih dari 2 ribu retweet dan ratusan komentar dari pengguna media sosial Twitter.
Memang ada kecenderungan umum bahwa dokter kini "alergi" terhadap isu sosial dan politik. Tapi, keterkaitan erat antara kondisi pasien dengan situasi terkini membuat dokter tak bisa menafikannya terlalu jauh. Apalagi dalam banyak penelitian, kondisi sosial kerap disebut sebagai salah satu faktor risiko penyebab.
Fenomena tersebut jelas bertolak belakang dengan periode pergerakan di banyak negara abad ke-19 dan ke-20. Ini mengingatkan pada apa yang dikatakan Rudolf Virchow, seorang dokter tahun 1800-an, yang menulis bahwa "politik tidak lain adalah obat dalam skala besar".
- Apakah Sumpah Hippokrates Sudah Tak Relevan dan Perlu Direvisi?
- Kiat-Kiat Ampuh bagi Seorang Dokter untuk Merencanakan Keuangan
Lebih dari satu abad berselang, kutipan tersebut bukan sekadar kata-kata kosong. Banyak dokter terlibat langsung di dua ranah tersebut. Sebut saja Che Guevara sang pemimpin pelawanan Kuba, Jose Rizal yang dieksekusi mati lantaran memimpin revolusi Filipina hingga Dr. Sun Yat-sen sebagai pendiri Republik Cina. Di Indonesia sendiri ada Cipto Mangunkusumo, tokoh organisasi pergerakan Boedi Oetomo yang juga lulusan STOVIA.
Lantas bagaimana dengan situasi aktivisme dokter terkini? Kecenderungannya memang meningkat selama pandemik COVID-19. David Oliver, seorang dokter asal Skotlandia, menulis bahwa dokter sekaligus aktivis telah berkampanye tanpa henti tentang banyak masalah.
Mulai dari kesehatan anak; pemberantasan tuberkulosis, malaria, dan polio; kesenjangan sanitasi dan kesehatan; kondisi kerja untuk staf yang merawat pasien; dan perawatan dan penelitian yang lebih baik untuk kelompok atau kondisi pasien yang terabaikan.
Selain itu, Oliver menulis bahwa tanpa advokasi oleh dokter-aktivis, jumlah perempuan yang bisa menempuh pendidikan di sekolah kedokteran akan jauh lebih sedikit. Tak akan tumbuh kesadaran tentang diskriminasi ras atau gender dalam kedokteran, dan tidak mungkin siswa yang datang dari kelas pekerja bisa menempuh pendidikan kedokteran.
Di AS sendiri, kesadaran dokter untuk mengambil sikap atas isu sosial meningkat seiring waktu. Situs KevinMD melaporkan bahwa berdasarkan survei, ada 9 dari 10 calon dokter yang menganggap advokasi sebagai bagian tak terpisahkan dari tugas profesional mereka.
Gagasan tentang dokter sekaligus advokasi sudah tertuang dalam Sumpah Hipokrates yakni "mencegah penyakit kapan pun (kita) bisa" dan memenuhi "kewajiban khusus kepada semua sesama manusia." Virchow pun pernah menulis bahwa "dokter adalah pengacara alami orang miskin, dan sebagian besar masalah sosial harus diselesaikan oleh mereka."
Beberapa organisasi medis kontemporer juga telah mengartikulasikan sikap tentang advokasi dokter dalam pernyataan misi dan kode profesional mereka. American Medical Association, misalnya, mengharuskan dokter untuk "mengadvokasi perubahan sosial, ekonomi, pendidikan dan politik yang memperbaiki penderitaan dan berkontribusi pada kesejahteraan manusia."
Sedang di Indonesia, pasal 12 KODEKI menegaskan bahwa "dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter wajib memerhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial-kultural pasiennya serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi sejati masyarakat."
Persepsi bahwa "advokasi" selalu berkonotasi politis memang keliru. Upaya untuk menyuarakan sesuatu jika ada ketimpangan adalah hal yang normal dalam masyarakat. Dokter menggunakan wawasan dan pengaruh mereka untuk memperbaiki kekeliruan di tengah masyarakat --utamanya pada perkara kesehatan-- dan mengadvokasi keadilan bagi pasien yang mereka layani.
Masalah tersebut sifatnya universal, dialami oleh semua orang, mulai dari para penduduk di London (Inggris) hingga Enarotali (Papua Tengah). Dokter dan perawat juga melakukan advokasi karena mereka merawat pasien yang sakit, menderita, dan meninggal karena kondisi sosial yang tidak adil.
Namun, peran advokasi lebih kompleks dari yang tertulis dalam Sumpah Hipokrates. Joshua Freeman, MD., pada 2012 menulis bahwa para dokter secara naluriah akan mendukung kebijakan "yang meringankan penderitaan dan berkontribusi pada kesejahteraan manusia."
Lebih jauh, Joshua menegaskan bahwa dokter adalah "orang sibuk" yang lebih sering melihat diri mereka hanya memberikan perawatan pasien langsung, alih-alih mengadvokasi untuk perubahan masyarakat yang sistemik.
Dokter sebagai penggerak inti aktivisme menurut Joshua dalam kondisi terkini mungkin saja tidak mencapai level yang hakiki. Tapi, bukan berarti mahasiswa kedokteran tak memiliki idealisme yang membentuk pandangan mereka atas isu-isu sosial.
Para dokter akan tetap memerhatikan kondisi di sekitarnya dan bersuara untuk hal-hal yang dianggapnya sebagai ketidakadilan. Sebab, mereka tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat.
Referensi :
- Edition 30 – all doctors should be social activists. HPHR Journal. (2022, August 12). Retrieved September 23, 2022, from https://hphr.org/30-article-edwads/
- Pallok, K. N., & Ansell, D. A. (2022, April 1). Should clinicians be activists? Journal of Ethics | American Medical Association. Retrieved September 23, 2022, from https://journalofethics.ama-assn.org/article/should-clinicians-be-activists/2022-04
- When doctors and nurses become activists. Partners In Health. (n.d.). Retrieved September 23, 2022, from https://www.pih.org/article/when-doctors-and-nurses-become-activists
- Fox, J., Rook, J., & Feuerbach, A. (2021, July 7). For future physician-activists: This is our lane. KevinMD.com. Retrieved September 23, 2022, from https://www.kevinmd.com/2019/03/for-future-physician-activists-this-is-our-lane.html
- Freeman, J. (2012, October 13). Physician advocacy, activism and politics. PNHP. Retrieved September 23, 2022, from https://pnhp.org/news/physician-advocacy-activism-and-politics/
- Oliver, D. (2020). David Oliver: Being labelled an “activist” is a badge of honour. BMJ, m4186. https://doi.org/10.1136/bmj.m4186
Log in untuk komentar